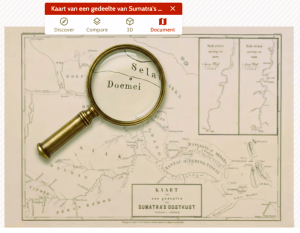KOLOM | Milestone Dumai, antara Kesaksian De Facto, Enigma Kartografis dan Kepastian De Jure

Infografis Peta Kaart van een gedeelte van Sumatra's Oostkust, Leiden University (1882).
Oleh Muhammad Natsir Tahar
Kota tidak bersuara tentang masa lalunya. Ia menyimpannya, diam-diam dan setia, bagai garis nasib yang terpahat pada telapak tangan: sebuah metafora yang dihunus oleh Italo Calvino, sang maestro fabel urban. Garis-garis itu bukan huruf mati, ia adalah jejak hidup: aliran sungai yang membelah bumi, lengkung jalan yang mengurai cerita, pola hunian yang membisikkan ingatan.
Dumai, seperti kota-kota lain, menyimpan sejarahnya bukan dalam kata, tetapi dalam guratan spasial, dalam nama yang melekat pada tanah, dalam arsip yang membisu menunggu untuk dibaca.
Menetapkan hari jadi sebuah kota pada hakikatnya adalah upaya mengenali detak jantung pertamanya. Di samping melaksanakan ritual administratif, adalah juga sebuah pencarian filosofis akan momen ketika suatu ruang berubah menjadi tempat, suatu kumpulan manusia berubah menjadi komunitas, dan suatu wilayah menemukan namanya dalam narasi besar sejarah. Itulah momen “sakral” yang kita buru, sebuah peristiwa yang menjadi pelantun kelahiran, bersifat transformatif dan konstitutif, mengubah yang faktual menjadi yang formal, yang hidup menjadi yang diakui.
Lihatlah bagaimana kota-kota lain menemukan nadinya. Jakarta terlahir dari sebuah tindakan penaklukan dan penamaan, Sunda Kelapa yang menjadi Jayakarta pada 1527, sebuah pernyataan politik yang berani. Purwakarta muncul dari ketukan palu hukum kolonial, sebuah Besluit yang mencatatnya dalam administrasi pada 1831.
Kediri bahkan lebih tua lagi, lahir dari aksara yang terpahat pada batu, prasasti yang menyebut namanya pada 804 Masehi. Setiap kota memilih bentuk kelahirannya sendiri: ada yang melalui kemenangan militer, keputusan politik, atau sekadar penyebutan tertulis pertama. Namun benang merahnya sama: mencari legitimasi dan asal-usul, mencari titik di mana sejarah mulai mencatat namanya.
Di Riau, kita menyaksikan permainan waktu dan ingatan yang serupa. Pekanbaru lahir dua kali: dari musyawarah adat Kerajaan Siak pada 1784, kemudian dari pengakuan Belanda sebagai gemeente pada 1906. Batam lahir dari secarik Titel Surat Kerajaan Riau-Lingga pada 1829. Tanjungpinang menyimpan dualitasnya: ia dikenang dalam heroisme Perang Riau 1784, tetapi secara resmi baru ditetapkan pada 1949. Di sini, kita belajar bahwa kelahiran bisa berlapis: ada yang tumbuh dari tanah tradisi, ada yang diresmikan oleh kekuasaan kolonial, dan ada yang diputuskan oleh negara modern. Setiap lapisan itu sah, masing-masing membentuk satu bagian dari jiwa kota.
Dalam keriuhan contoh-contoh itu, pencarian “Milestone Dumai” menemukan konteksnya. Ia berjalan di jalur yang sama dengan Pekanbaru dan Batam, mencari legitimasi dari dalam rahim tradisi Kesultanan Siak dan Riau Lingga. Namun, jejak kelahiran Dumai tidaklah tunggal; ia terhampar dalam beberapa lapisan waktu, masing-masing mengungkap secercah cahaya tentang bagaimana nama “Doemei” perlahan lahir ke dalam kesadaran kartografis dan politik.
Pertama, ada Catatan J.S.G. Gramberg tahun 1864: sebuah manuskrip awal yang menyebut “Dumai” secara eksplisit dan berulang, bagai seorang pengelana yang mencatat detak kehidupan sebuah tempat yang telah hidup. Ini adalah kesaksian de facto: bukti bahwa komunitas itu telah ada, bernapas, dan diakui dalam keseharian. Namun, apakah cukup sebuah catatan perjalanan untuk melahirkan sebuah entitas politik?
Kemudian, munculnya enigma kartografis antara 1875 dan 1882. Peta Leiden 1875 masih membisu, tidak ada secercah nama “Doemei” yang tertoreh. Namun, tujuh tahun kemudian, pada 1882, nama itu tiba-tiba muncul, tercatat dengan ejaan kolonial “Doemei”, seakan-akan dunia tata ruang baru saja mengakui keberadaannya. Apa yang terjadi dalam interval waktu yang sunyi itu?
Di sini, sejarah berbisik tentang sebuah peristiwa formal yang mungkin terjadi: sebuah surat resmi dari Kerajaan Siak, sebuah pengakuan, sebuah legitimasi yang memungkinkan Belanda, yang selalu berpedoman pada sumber resmi kerajaan untuk akhirnya mencantumkan nama itu di peta mereka. Sayangnya, dokumen itu masih hilang, tersembunyi di suatu tempat dalam lipatan arsip yang gelap, meninggalkan kita dengan pertanyaan: peristiwa politik apakah yang membuka jalan bagi pencantuman nama itu?
Dan akhirnya, ada Korpus 1882–1884 [versi yang dianjurkan AI]: sebuah kumpulan dokumen yang memadatkan waktu menjadi momen krusial. Di dalamnya, ada laporan perjalanan J.A. van Rijn van Alkemade (1884), yang mengurai kehidupan Dumai dengan lebih intim; ada kemungkinan surat-menyurat, perjanjian, atau keputusan yang mengukuhkan “Doemei” bukan hanya sebagai nama di peta, tetapi sebagai entitas politik yang diakui dalam hubungan antara Siak dan Belanda. Inilah momen de jure yang mungkin kita cari: saat yang faktual berubah menjadi yang formal, saat yang hidup memperoleh pengakuan resmi.
Ketiga lapisan ini [Gramberg 1864, teka-teki peta 1875–1882, dan korpus 1882–1884] tidak diindentifikasi sebagai versi yang saling meniadakan, melainkan gerbang-gerbang waktu yang menuntun kita semakin dekat ke pusat kelahiran. Mereka adalah tahapan dalam proses panjang pengakuan: dari kesaksian etnografis, melalui legitimasi kartografis, hingga pengukuhan politik. Masing-masing membawa kebenarannya sendiri, dan bersama-sama mereka merajut sebuah narasi yang lebih utuh tentang bagaimana sebuah tempat perlahan-lahan menemukan namanya dalam sejarah.
Dalam keriuhan bukti-bukti itulah, filsafat sejarah dan hasrat manusia berkumpul. Menetapkan hari jadi adalah upaya membangun locus, tempat bersemayamnya ingatan kolektif, sebagaimana dikatakan Aldo Rossi. Tanpa titik awal yang disepakati, ingatan itu melayang, narasi terpecah, identitas kehilangan pijakan. Sebuah tanggal yang disakralkan menjadi jantung dari identitas kota, sumber kebanggaan, dan pembeda dari yang lain. Ia memberi legitimasi dan rasa kontinuitas: kita bukan entitas yang tiba-tiba muncul, melainkan anak dari sejarah panjang yang patut dibanggakan.
Namun, ada ketegangan diam-diam antara dua pengakuan: de facto dan de jure. Yang de facto adalah napas kehidupan: komunitas Dumai yang sudah ada, dicatat oleh Gramberg pada 1864, hidup dalam struktur Siak. Yang de jure adalah tulang administrasi: keputusan resmi, perjanjian bertinta, UU No. 16 Tahun 1999 yang secara hukum melahirkan Kota Dumai. Keduanya penting. Yang satu adalah daging, yang lain adalah kerangka. Pencarian kita adalah upaya merajut keduanya: menemukan momen di mana napas kehidupan itu pertama kali memperoleh kerangka hukumnya, momen di mana “Doemai” yang hidup diabadikan menjadi “Dumai” yang diakui.
Inilah esensi dari proyek ini: mengembalikan memori yang tercecer, membangun jiwa dari arsip yang membisu. Sebab, kota pada akhirnya adalah ingatan kolektif rakyatnya, ingatan yang melekat pada tempat, pada nama, pada dokumen. Dengan menemukan garis kelahiran yang tepat pada telapak tangan sejarah, kita tidak sekadar menetapkan tanggal. Kita sedang menuliskan kembali puisi panjang tentang asal-usul, memberikan suara pada yang bisu, dan mengukir jiwa untuk sebuah kota yang terus berjalan menuju masa depannya. ~