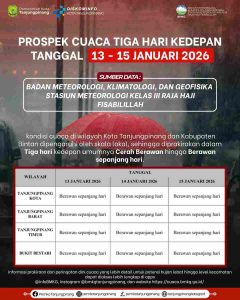Paradoks Otonomi Daerah: Mengapa Kemiskinan di Tanjungpinang Masih Bertahan Meski Sudah Ada Desentralisasi

Oleh Haura Faseha Afda
Dua puluh lima tahun setelah desentralisasi diterapkan, semakin terlihat bahwa otonomi daerah tidak otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanjungpinang, yang secara normatif diposisikan sebagai pusat kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, justru menampilkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yang selama ini diklaim sebagai solusi atas ketimpangan pembangunan. Jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan ribu jiwa, disertai tingkat pengangguran yang tetap tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Tanjungpinang tidak sejalan dengan harapan maupun janji kebijakan awal.
Persoalan kemiskinan yang terus bertahan sangat berkaitan dengan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Defisit anggaran yang berulang, rendahnya Pendapatan Asli Daerah, dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat menempatkan pemerintah kota dalam posisi yang sulit untuk merancang program pengurangan kemiskinan secara efektif. Keterbatasan dana menghambat pelaksanaan program yang sebenarnya penting bagi masyarakat, sehingga kemiskinan bukan hanya berulang tetapi berkembang menjadi masalah struktural yang semakin sulit diatasi.
Pada saat yang sama, kewenangan yang diberikan melalui desentralisasi tidak diimbangi dengan alokasi dana yang memadai. Program seperti PKH, BLT, pemberdayaan UMKM, serta layanan pendidikan dan kesehatan memang krusial, tetapi tanpa kapasitas fiskal dan birokrasi yang kuat, program tersebut tidak mampu menghasilkan perubahan berarti. Kondisi ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi, terutama di daerah yang sejak awal telah berhadapan dengan ketimpangan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja formal, dan dominasi sektor informal.
Lebih problematisnya, ketika daerah menghadapi kompleksitas persoalan yang meningkat, pemerintah pusat justru melakukan pemangkasan anggaran melalui kebijakan efisiensi. Penurunan alokasi dana ini menjadi beban tambahan bagi daerah seperti Tanjungpinang yang sangat bergantung pada transfer pusat. Kebijakan tersebut menciptakan paradoks: otonomi diberikan, namun ruang fiskal untuk melaksanakan pembangunan justru semakin menyempit. Pemerintah daerah tetap dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat, namun terikat oleh mekanisme fiskal yang rigid dan tidak sejalan dengan esensi desentralisasi.
Indikator pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli juga menunjukkan stagnasi. Keterbatasan anggaran membuat layanan sosial tidak dapat dijalankan optimal, sehingga kebutuhan dasar banyak kelompok masyarakat terabaikan. Ketimpangan sosial pun semakin menguat karena pemerintah daerah tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengatasinya. Situasi ini menegaskan bahwa desentralisasi belum memberikan dampak signifikan bagi Tanjungpinang, karena kewenangan yang diberikan tidak ditopang oleh kapasitas fiskal yang sesuai.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik desentralisasi selama ini lebih berfokus pada pembagian kewenangan administratif daripada memastikan kesiapan fiskal dan kelembagaan daerah. Dengan kapasitas anggaran yang terbatas, standar pelayanan publik sulit dipenuhi secara konsisten. Alih-alih mengurangi ketimpangan, desentralisasi yang tidak disertai sumber daya memadai justru memperlebar jurang antara daerah yang kuat dan yang lemah. Tanjungpinang menjadi contoh konkret dari ketidakseimbangan tersebut.
Mencermati kompleksitas persoalan yang muncul, diperlukan evaluasi ulang terhadap cara desentralisasi dioperasikan selama ini. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa desentralisasi hanya efektif jika wilayah didukung birokrasi profesional, tata kelola anggaran yang transparan, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Pemerintah daerah juga harus memiliki ruang untuk memperkuat PAD melalui diversifikasi ekonomi, bukan sekadar menjadi penerima pasif transfer pusat. Tanpa langkah tersebut, daerah akan tetap terjebak dalam ketergantungan fiskal yang melemahkan daya saing dan kapasitas pelayanan publik.
Situasi Tanjungpinang memperlihatkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kekuatan fiskal, kapasitas institusional, dan kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif. Otonomi yang diberikan tanpa dukungan sumber daya yang memadai hanya menciptakan wacana kemandirian tanpa substansi. Jika desentralisasi ingin berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, maka kolaborasi yang lebih selaras antara pemerintah pusat dan daerah harus dibangun kembali. Tanpa perbaikan struktural tersebut, desentralisasi berisiko terus menghasilkan paradoks kebijakan kewenangan diperluas, tetapi kemampuan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan tetap terbatas.
Haura Faseha Afda___adalah Mahasiswa UMRAH Jurusan Ilmu Pemerintahan